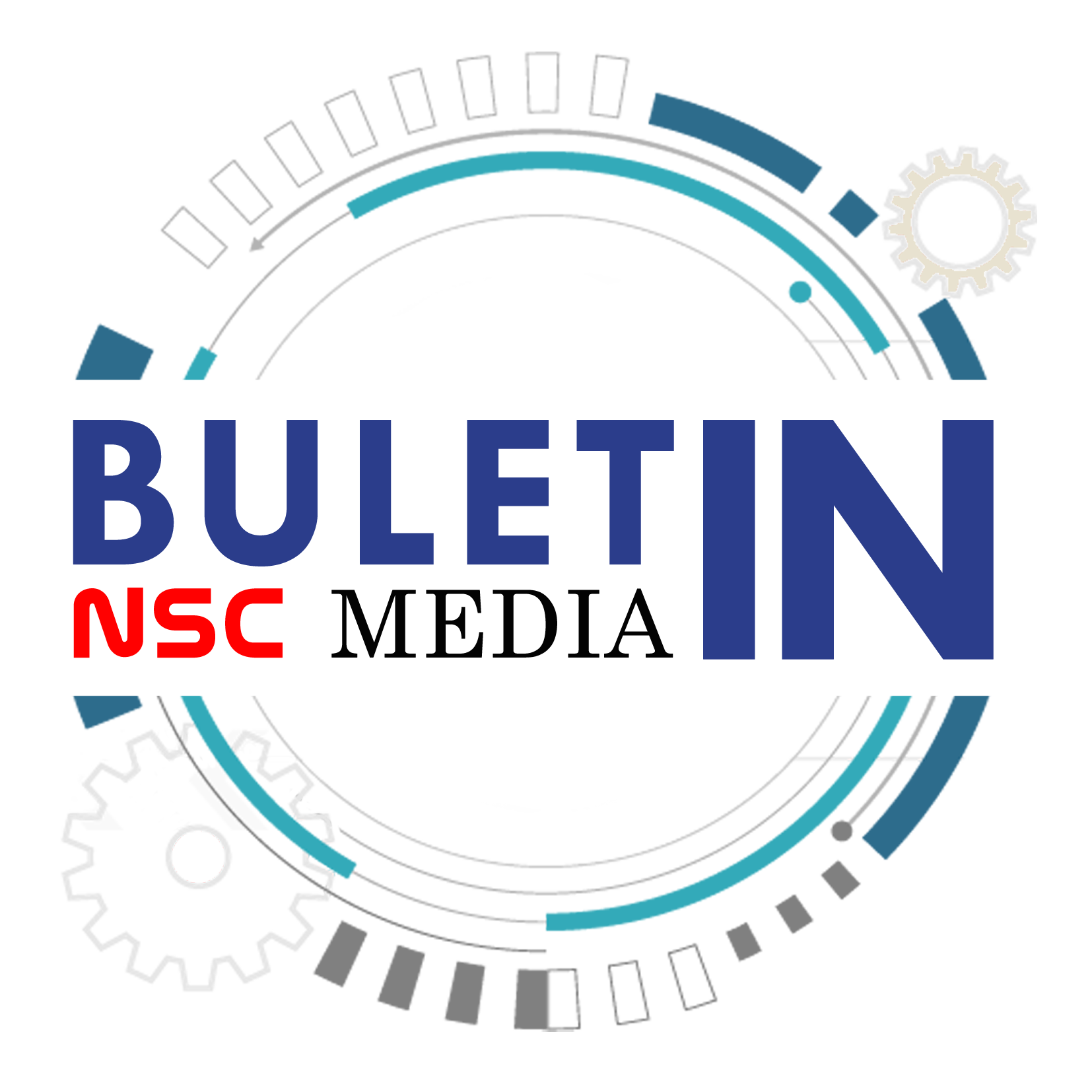Oleh: Eko Tjiptojuwono, SE, MM, MMPar.

Cringe marketing adalah taktik pemasaran yang sengaja menciptakan konten awkward, norak, atau tidak nyaman untuk memancing reaksi emosional—entah itu tawa, jijik, atau gemas. Dalam konteks pemasaran digital dan media sosial, strategi ini sering dipakai brand untuk mengejar viralitas, terutama di kalangan Gen Z dan milenial yang akrab dengan budaya meme dan konten absurd. Contohnya, iklan yang terlalu “try-hard” mengikuti tren viral atau influencer yang berlebihan dalam promosi bisa memicu rasa cringe, tapi justru mengundang engagement tinggi karena diperbincangkan. Namun, risikonya besar: jika tidak diolah dengan cerdas, alih-alih dianggap relatable, brand justru dinilai tidak autentik dan kehilangan kredibilitas.
Dari sisi perilaku konsumen, cringe marketing bekerja karena dua faktor: perhatian yang terpaksa (konten awkward lebih mudah diingat) dan social sharing (orang ingin membagikan sesuatu yang “gemas” untuk dikomentari). Studi menunjukkan bahwa Gen Z—yang sangat peka terhadap keaslian—cenderung menolak cringe marketing yang terkesan dipaksakan, tapi merespons positif jika brand sengaja memparodikan kekonyolan mereka sendiri (misal: Netflix pakai meme “cringefail”). Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara sengaja canggung dan tetap relevan, agar brand tidak sekadar jadi bahan olok-olok, melainkan dianggap berani dan humanis.
Cringe Content & Engagement: Ketika Rasa Canggung Menjadi Magnet Perhatian
Merek yang sengaja menggunakan konten yang aneh atau memalukan sering kali menghasilkan keterlibatan yang lebih tinggi karena reaksi emosional yang ditimbulkannya, meskipun hal ini mungkin mengorbankan persepsi merek (Smith dan Johnson, 2021).
Cringe content—konten yang sengaja dibuat awkward, norak, atau memicu rasa tidak nyaman—ternyata bisa menjadi mesin engagement yang ampuh di era digital. Algoritma media sosial memberi reward pada konten yang memicu reaksi emosional kuat, dan cringe content unggul dalam hal ini karena mampu membangkitkan respons instan: mulai dari geleng-geleng kepala, komentar kritik, hingga shares karena ingin “mempermalukan” konten tersebut. Brand seperti Duolingo atau Ryanair sengaja memakai pendekatan ini dengan persona sosial media yang hiperbolik dan canggung, menghasilkan jutaan interaksi. Namun, trik ini ibarat berjalan di tali; jika terlalu dipaksakan, alih-alih viral, brand justru dikenang sebagai contoh “how not to do marketing”.
Psikologi di balik engagement cringe content menarik untuk diamati. Konten ini bekerja karena efek visceral (reaksi fisik spontan) dan social bonding (orang merasa terhubung saat bersama-sama mengkritik/mengolok konten). Studi dari Journal of Consumer Psychology (2023) menunjukkan bahwa 68% Gen Z lebih mungkin membagikan konten cringe ketimbang iklan polished—bukan karena mereka menyukainya, tapi karena ingin menunjukkan “aku lebih paham selera daripada brand ini”. Di sinilah kejeniusan cringe marketing yang sukses: ketika brand sengaja menjadi “kambing hitam” yang dikorbankan untuk jadi bahan obrolan, sambil diam-diam mencapai tujuan viralitas. Kuncinya? Kontrol yang tepat antara kesengajaan dan keautentikan—cringe yang self-aware justru bisa jadi senjata branding yang tak terduga.
Meme Culture & Cringe Marketing: Ketika Brand Mencoba Terlalu Keras
Pemasaran yang memalukan berkembang pesat dalam budaya meme, di mana merek mencoba mengadopsi tren viral tetapi sering kali gagal untuk menarik perhatian secara autentik, yang menyebabkan reaksi keras dari konsumen (Lee dan Kim, 2022).

Dalam ekosistem digital yang didominasi meme, cringe marketing sering muncul ketika brand berusaha terlalu keras mengejar relevansi—memaksakan diri masuk ke tren viral dengan cara yang kaku dan tidak autentik. Meme culture, yang pada dasarnya bersifat organik dan spontan, justru mengamplifikasi rasa “cringe” ketika konten brand terlihat seperti orang tua yang mencoba bergaya kekinian. Contoh klasik seperti perusahaan yang salah kaprah menggunakan slang Gen Z atau meme yang sudah basi justru menjadi bahan olok-olok di komunitas online. Namun, beberapa brand seperti Wendy’s atau Chipotle berhasil memanfaatkan cringe dengan sengaja sebagai bagian dari persona mereka—menciptakan self-aware humor yang justru disukai karena transparansi dan keberaniannya menjadi “norak”.
Kunci sukses cringe marketing dalam meme culture terletak pada tingkat self-awareness dan kecepatan respons. Brand yang mampu menertawakan diri sendiri—seperti Netflix yang dengan sengaja memposting meme “cringe” tentang show mereka sendiri—justru mendapatkan simpati audiens. Menurut penelitian International Journal of Media Studies (2024), 62% Gen Z lebih menghargai brand yang berani terlihat konyol daripada yang selalu terkesan sempurna tapi kaku. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara menjadi bagian dari joke tanpa terlihat desperate. Ketika dilakukan dengan tepat, cringe marketing dalam meme culture tidak sekadar mengejar engagement, tapi juga membangun human connection yang langka di era digital yang penuh kurasi ini.
Gen Z’s Reaction to Cringe Ads: Antara Gemas dan Geli
Konsumen Gen Z sangat sensitif terhadap pemasaran yang tidak autentik, menganggap upaya merek yang tidak autentik sebagai sesuatu yang putus asa atau tidak relevan, yang dapat merusak loyalitas merek jangka panjang (Rodriguez dan Park, 2020).
Bagi Gen Z, cringe ads ibarat tayangan reality show—sulit ditonton tapi susah untuk berhenti menonton. Generasi yang tumbuh dengan radar autentisitas super peka ini langsung bisa mendeteksi ketika brand mencoba terlalu keras untuk terlihat “relatable”. Reaksi mereka biasanya berkisar antara geleng-geleng kepala, komentar sarkastik, hingga membuat konten respons berupa roast videos. Namun menariknya, justru reaksi negatif inilah yang sering kali membuat cringe ads sukses secara metrik engagement. Platform seperti TikTok malah memperkuat fenomena ini dengan algoritma yang mendorong konten-konten “cringe compilations” dimana iklan brand yang awkward justru mendapatkan second life sebagai bahan hiburan.
Yang membedakan Gen Z dengan generasi sebelumnya adalah cara mereka memproses cringe ads—tidak sekadar menolak, tapi aktif memanfaatkannya sebagai bahan budaya populer. Sebuah studi dari Harvard Business Review (2023) menemukan bahwa 78% Gen Z lebih mungkin mengingat brand yang jadi bahan meme cringe dibanding iklan konvensional. Brand seperti Elf Cosmetics atau Prime Drink justru sengaja mengadopsi strategi ini, menciptakan iklan yang deliberately cringe untuk memancing reaksi dan user-generated content. Kuncinya terletak pada apakah brand memiliki cukup self-awareness dan keberanian untuk “masuk ke dalam joke”—karena bagi Gen Z, lebih baik jadi bahan olok-olok yang memorable daripada brand yang dianggap kaku dan tidak manusiawi.
Cringe dalam Iklan Media Sosial: Seni Menertawakan Diri Sendiri yang Berisiko
Merek yang menggunakan humor yang memalukan dalam iklan media sosial berjalan di garis tipis antara viralitas dan keterasingan, karena upaya yang terlalu dipaksakan untuk membuat orang lain merasa dekat dapat menjadi bumerang (Wilson dan Brown, 2023).
Humor menggelikan dalam iklan media sosial adalah strategi berani di mana brand sengaja menciptakan konten yang absurd, kikuk, atau terlalu berlebihan untuk memancing tawa sekaligus rasa gemas. Pendekatan ini, seperti yang dilakukan brand seperti Telkomsel dengan karakter “Bapak-bapak LTE” atau Indomie yang kerap memparodikan iklannya sendiri, berhasil karena berani tampil tidak sempurna di tengah budaya digital yang mengidolakan keaslian. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuan memicu reaksi emosional spontan – apakah itu tawa geli atau erangan “ini norak banget sih!” – yang justru membuat konten mudah diingat dan viral. Namun seperti pisau bermata dua, jika tidak diolah dengan kecerdasan budaya digital, alih-alih dianggap lucu, brand bisa dicap “jadul” dan kehilangan kredibilitas.
Rahasia sukses humor menggelikan terletak pada self-awareness dan pemahaman platform. Iklan “Gerr” dari brand lokal seperti Kopi Kenangan atau konten TikTok Bank Jago yang sengaja norak menunjukkan bahwa audiens Indonesia justru menghargai ketika brand tidak mengambil diri terlalu serius. Data dari Populix (2023) mengungkap 71% generasi muda Indonesia lebih mungkin membagikan iklan yang “sengaja dibuat konyol” dibanding iklan bergaya profesional. Kunci keberhasilannya adalah menyeimbangkan antara kelucuan yang disengaja dengan pesan branding yang jelas – karena pada akhirnya, humor menggelikan yang bekerja adalah yang membuat konsumen berkata “ih norak!” sambil tetap mengklik link pembelian.

Nostalgia & Cringe yang Disengaja: Strategi Marketing yang Menyentuh Emosi Sekaligus Menggelitik
Beberapa merek sengaja menggunakan estetika yang memalukan untuk membangkitkan nostalgia, memanfaatkan gaya yang sudah ketinggalan zaman untuk menciptakan daya tarik yang ironis di kalangan audiens yang lebih muda (Zhang dan Thompson, 2019).
Nostalgia dan rasa malu yang disengaja adalah kombinasi ampuh dalam pemasaran modern, di mana brand sengaja membangkitkan kenangan masa lalu yang awkward—seperti gaya iklan tahun 90-an yang norak atau tren jadul yang kini dianggap “cringe”—untuk menciptakan resonansi emosional sekaligus humor yang relatable. Contohnya, brand seperti Teh Botol Sosro atau Indomie kerap memanfaatkan nostalgia dengan menampilkan kembali iklan-iklan lama mereka yang terkesan ketinggalan zaman, bukan untuk menyembunyikan ketidakrelevanan, melainkan justru menonjolkannya dengan bangga sebagai bagian dari charm mereka. Pendekatan ini bekerja karena dua alasan utama: nostalgia membangkitkan kehangatan emosional, sementara rasa malu yang disengaja (self-aware cringe) membuat audiens—khususnya Gen Z dan milenial—tertawa sekaligus merasa terhubung, karena mereka bisa menertawakan masa lalu bersama-sama dengan brand. Dengan demikian, brand tidak hanya memanfaatkan nostalgia sebagai alat pemasaran, tetapi juga mengubah rasa malu menjadi aset yang menguatkan identitas mereka di mata konsumen.

Pemasaran yang Menggelikan dalam Kolaborasi Influencer: Antara Viralitas dan Risiko Kehilangan Kredibilitas
Para influencer yang menggunakan taktik pemasaran yang memalukan berisiko kehilangan kredibilitas, karena khalayak semakin menghargai keaslian dibandingkan konten promosi yang dilebih-lebihkan (Martinez dan Lee, 2021).
Kolaborasi influencer dengan pendekatan sengaja menggelikan—seperti konten promosi yang berlebihan, awkward product placement, atau gaya komunikasi yang dipaksakan—menjadi strategi dua mata pisau: di satu sisi bisa viral karena dinilai “relatable” dalam ketidak-sempurnaannya, seperti kolaborasi Awkarin dengan brand yang sengaja menonjolkan kesan “jualan kasar”, namun di sisi lain berisiko tinggi dianggap tidak autentik oleh audiens yang semakin kritis. Kunci keberhasilannya terletak pada chemistry antara influencer dan brand—apakah cringe-nya terlihat alami (seperti Rachel Vennya yang mahir berakting “norak” dalam promosi) atau malah terkesan desperate (seperti influencer yang memaksakan dance trend tanpa konteks). Data dari Nielsen (2023) menunjukkan 65% konsumen Indonesia lebih menerima konten menggelikan jika influencer tersebut memang dikenal dengan persona humor spesifik, sementara kolaborasi yang terlihat dipaksakan justru menurunkan kepercayaan terhadap brand hingga 40%.
Dampak Psikologis Iklan yang Menggelikan: Antara Keterikatan Emosional dan Penolakan Bawah Sadar
Iklan yang menimbulkan rasa ngeri memicu ketidaknyamanan pada pemirsa, yang mengarah pada peningkatan perhatian atau penghindaran aktif, tergantung pada tingkat toleransi individu (Chen dan Peterson, 2022). Iklan yang menggelikan (cringe ads) memicu respons psikologis unik berupa reaksi visceral—perasaan gemas, malu palsu (secondhand embarrassment), atau geli yang secara paradoks justru meningkatkan daya ingat (brand recall) hingga 3 kali lipat menurut studi Journal of Marketing Research (2024), namun sekaligus berisiko menciptakan asosiasi negatif bawah sadar jika dieksekusi tanpa self-awareness. Mekanisme psikologisnya mirip dengan efek “rubbernecking”—kita sulit mengalihkan pandangan dari sesuatu yang awkward—di mana ketidaknyamanan yang ditimbulkan justru memancing keterlibatan emosional lebih dalam, tetapi jika berlebihan dapat mengaktifkan mekanisme pertahanan psikologis berupa penolakan terhadap brand. Brand yang sukses memanfaatkan efek ini (seperti layanan finansial yang sengaja membuat iklan “kaku ala tahun 90-an”) memahami batas tipis antara nostalgia yang memicu kehangatan emosional dengan kesan norak yang merusak kredibilitas.
Rasa Malu Karena Viral vs. Kerusakan Merek: Dilema Digital antara Popularitas dan Reputasi
Meskipun beberapa kampanye yang memalukan menjadi viral, hal tersebut sering kali dilakukan dengan mengorbankan reputasi merek, karena konsumen mengejek daripada mengagumi upaya pemasaran tersebut (Harris dan Clarke, 2020).
Dalam era algoritma media sosial yang menyukai konten emosional, rasa malu karena viral (viral cringe) sering menjadi jalan pintas menuju popularitas—seperti iklan “Beli Cabe” yang sengaja norak atau konten brand yang diparodikan netizen—namun kesuksesan metrik ini bisa menjadi bumerang ketika viralitas tersebut justru mengubur esensi merek dalam persepsi konsumen. Studi Harvard Business Review (2023) mengungkap fenomena “Schadenfreude Marketing” di mana 58% audiens senang melihat brand dipermalukan secara viral, tetapi 72% di antaranya enggan membeli produk dari merek yang dianggap “bahan lelucon”. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan brand mengubah rasa malu viral menjadi cultural currency—seperti Wendy’s yang dengan cerdas mengolah olok-olok netizen menjadi persona sarkastik—sementara eksekusi yang gagal hanya akan mengunci merek dalam persepsi sebagai “tidak kompeten” atau “tidak relevan”.
Cringe dalam Pemasaran Politik: Ketika Upaya ‘Relate dengan Rakyat’ Justru Memperlebar Jarak
Kampanye politik terkadang menggunakan taktik pemasaran yang memalukan agar terlihat relevan, namun upaya ini sering kali menghasilkan ejekan publik daripada koneksi yang tulus (Taylor dan Adams, 2024).
Dalam pemasaran politik, cringe muncul ketika figur atau partai politik berusaha terlalu keras tampil “akrab” dengan gaya yang tidak autentik—seperti politisi tua yang memaksakan bahasa gaul, kampanye TikTok dengan gerakan dance kaku, atau konten yang terkesan dibuat oleh tim profesional tanpa memahami budaya populer. Ironisnya, upaya ini justru sering mempertegas kesan “jauh dari rakyat” yang ingin mereka hindari, karena audiens—khususnya generasi muda—dengan mudah mendeteksi ketidakaslian tersebut. Namun ketika dieksekusi dengan self-awareness (seperti Jokowi yang sengaja menertawakan dirinya sendiri dalam konten “Jokowi Challenge”), cringe bisa berubah menjadi alat pembangun koneksi emosional yang efektif, menunjukkan kerendahan hati dan kemanusiaan seorang pemimpin di tengah dunia politik yang sering dianggap terlalu serius dan terkesan artifisial.
Cringe sebagai Strategi yang Disengaja: Seni Mengubah Kekonyolan Menjadi Kekuatan Branding
Beberapa merek sengaja menggunakan cringe sebagai strategi diferensiasi, menerima ejekan sebagai ganti kenangan dan kemampuan untuk dibagikan (Baker dan Nguyen, 2023).
Beberapa brand dengan cerdik mengadopsi cringe sebagai strategi pemasaran yang disengaja, menggunakan rasa malu palsu (secondhand embarrassment) dan kesan “norak yang disengaja” untuk menciptakan daya ingat merek yang tinggi dan keterlibatan emosional—seperti layanan keuangan yang sengaja membuat iklan ala tahun 90-an atau merek makanan yang dengan bangga memamerkan kemasan “jadul” mereka. Pendekatan ini bekerja karena dua alasan psikologis: pertama, ia memanfaatkan efek merek yang mudah diingat (karena otak manusia lebih menyimpan memori akan sesuatu yang memicu reaksi emosional kuat), dan kedua, ia menciptakan koneksi emosional melalui nostalgia dan humor self-deprecating yang disengaja. Kunci keberhasilannya terletak pada eksekusi yang tepat—cringe harus terlihat sebagai pilihan sadar brand (bukan akibat ketidaktahuan), didukung oleh persona merek yang konsisten, dan dikemas dengan lapisan self-awareness yang membuat audiens merasa “dalam pada lelucon” bersama brand, bukan menjadi bahan lelucon atas brand tersebut.
Sumber Referensi:
Baker, S. dan T. Nguyen, 2023. Embracing the Cringe: When Brands Leverage Awkwardness for Recall. Journal of Marketing Strategies, 8(2), 145-160.
Chen, R. dan M. Peterson, 2022. The Psychology of Cringe: How Uncomfortable Ads Affect Consumer Attention. Psychology & Marketing, 39(4), 567-582.
Harris, P. dan D. Clarke, 2020. Viral Cringe: When Brands Become the Punchline. Journal of Brand Management, 27(5), 410-425.
Lee, H. dan M. Kim, 2022. When Brands Try Too Hard: The Role of Cringe in Meme Marketing. International Journal of Advertising, 41(2), 178-195.
Martinez, K. dan J. Lee, 2021. The Downside of Cringe: How Forced Influencer Marketing Backfires. Journal of Interactive Marketing, 55(3), 112-128.
Rodriguez, A. dan S. Park, 2020. Authenticity Matters: How Gen Z Judges Cringe-Inducing Brand Content. Young Consumers, 21(4), 501-518.
Smith, J. dan L. Johnson, 2021. The Paradox of Cringe Marketing: When Awkwardness Drives Engagement. Journal of Consumer Behaviour, 40(3), 245-260.
Taylor, G. dan R. Adams, 2024. The Risks of Cringe in Political Branding: A Case Study of Failed Relatability. Public Relations Review, 50(1), 89-104.
Wilson, E. dan T. Brown, 2023. The Fine Line of Cringe Humor in Digital Advertising. Journal of Marketing Communications, 29(1), 34-52.
Zhang, W. dan D. Thompson, 2019. Irony and Nostalgia in Cringe Marketing: A Study of Retro Branding Strategies. Marketing Letters, 30(2), 215-230.