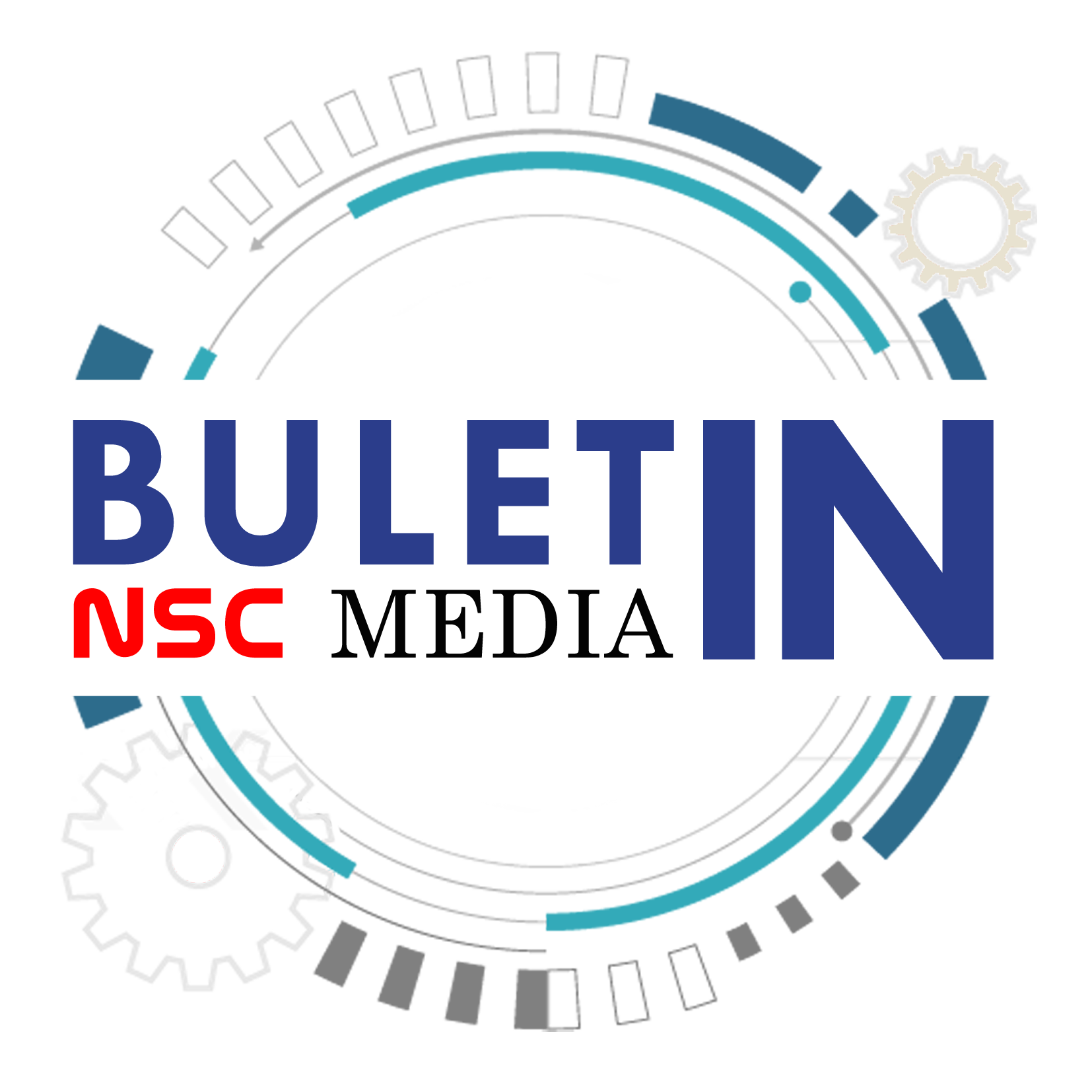Oleh: Gunaningtyas Ayu L.P., S.Pd M.Par

Di era digitalisasi pariwisata, bahasa menjadi kunci utama dalam menciptakan pealaman wisata yang autentik. Menurut laporan UNWTO (2023), 68% wisatawan internasional mengakui bahwa interaksi menggunakan bahasa lokal membuat perjalanan mereka lebih bermakna. Fenomena ini memunculkan tantangan sekaligus peluang bagi destinasi wisata di Indonesia. Di satu sisi, bahasa daerah seperti Bahasa Jawa, Sunda, atau Bali menjadi daya tarik budaya yang unik. Studi Journal of Travel Research (2022) membuktikan bahwa promosi wisata yang mengintegrasikan bahasa lokal mampu meningkatkan minat kunjungan hingga 40%. Contohnya, Kampung Inggris di Pare, Jawa Timur, sukses menarik wisatawan domestik dan mancanegara dengan menggabungkan pembelajaran bahasa Inggris dan wisata edukasi. Sementara itu, Suku Baduy di Banten mempertahankan bahasa Sunda Kuno sebagai bagian dari paket tur budaya mereka, menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan warisan yang perlu dilestarikan.
Namun, kemajuan teknologi turut mengubah pola komunikasi wisatawan. Survei Google Travel Insights (2024) mengungkapkan bahwa 75% wisatawan mengandalkan aplikasi translator seperti Google Translate selama liburan. Meski praktis, teknologi ini belum sepenuhnya menggantikan sentuhan manusia. Sebanyak 62% responden mengaku lebih puas berinteraksi langsung dengan staf destinasi yang fasih berbahasa asing. Inovasi seperti robot penerjemah 50 bahasa di Bandara Changi Singapura atau aplikasi Augmented Reality (AR) “BahasaKita” di Bali yang menerjemahkan menu makanan via kamera smartphone menjadi solusi hybrid. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi teknologi dan kehangatan interaksi manusia.
Bahasa juga berperan sebagai soft diplomacy dalam membangun citra pariwisata. Pelatihan bahasa bagi masyarakat sekitar destinasi, seperti yang dilakukan Desa Penglipuran di Bali, terbukti meningkatkan pendapatan warga sekaligus mengurangi miskomunikasi budaya. Misalnya, wisatawan Jepang kerap merasa tersinggung dengan penggunaan kata “tidak” yang dianggap terlalu kasar, sehingga pemandu wisata dilatih menggunakan frasa alternatif seperti “mohon dimaklumi”. Di Australia, program “Tourism Bahasa” yang diinisiasi Kedutaan RI Canberra (2023) telah menarik 23.000 peserta untuk mempelajari Bahasa Indonesia, membuka potensi kunjungan wisatawan yang lebih personal. Tak kalah menarik, konten TikTok berhashtag #SundaneseChallenge berhasil meraih 4,8 juta views dari calon wisatawan mancanegara, membuktikan bahwa bahasa daerah bisa menjadi alat pemasaran digital yang efektif.
Di tengah maraknya platform seperti Instagram dan TikTok, kreator konten menjadi ujung tombak promosi bahasa lokal secara kreatif. Akun @DiscoverSumba, misalnya, viral dengan video pendek berjudul “5 Kata Bahasa Sumba yang Wajib Kamu Tahu Sebelum Liburan”. Konten ini tidak hanya meraih 1,2 juta views dalam seminggu, tetapi juga mendorong kenaikan kunjungan ke Sumba sebesar 15% (Data Kemenparekraf, 2024). Kolaborasi antara pemerintah daerah dan influencer seperti Febby Rastanty—yang mempopulerkan istilah Bali seperti “melali” (jalan-jalan) melalui vlog perjalanannya—menunjukkan bahwa bahasa daerah bisa “dijual” sebagai konten edukatif yang menghibur. Tantangannya adalah menjaga akurasi makna kata agar tidak terdistorsi oleh tren semata.
Pariwisata juga bisa menjadi penyelamat bahasa yang terancam punah. UNESCO mencatat 12 bahasa daerah di Indonesia berstatus critically endangered, termasuk Bahasa Tola di Flores dan Bahasa Hukumon di Halmahera. Di Toraja, Festival Bahasa Ibu mengajak wisatawan belajar frasa dasar Bahasa Toraja sambil menyusuri kubur batu, sementara EcoTravel Indonesia mengalokasikan 10% pendapatan tur Papua untuk dokumentasi bahasa Suku Arfak. Contoh global seperti revitalisasi Bahasa Maori di Selandia Baru melalui pertunjukan haka menjadi bukti bahwa integrasi bahasa dengan budaya bisa memicu kebanggaan lokal dan ketertarikan global.
Kemampuan berbahasa asing ternyata berdampak langsung pada kesejahteraan pelaku wisata. Survei Bank Indonesia (2023) di Yogyakarta menemukan bahwa pemandu wisata yang menguasai Bahasa Jepang atau Mandarin memperoleh pendapatan 2x lipat dibandingkan yang hanya berbahasa Indonesia. Kafe-kafe di Ubud, Bali, bahkan memberi diskon 10% bagi wisatawan yang memesan menggunakan Bahasa Bali dasar, seperti “tiang pesan kopi” (saya pesan kopi). Strategi ini tidak hanya mendorong pembelajaran bahasa, tetapi juga menciptakan ikatan emosional antara wisatawan dan destinasi.
Menu makanan kini menjadi media pelestarian bahasa lokal. Restoran “Nusantara Rasa” di Jakarta menyajikan hidangan khas Papua dengan deskripsi berbahasa Dani, seperti “Wam Hitam” (nasi hitam) dan “Pigogo” (ulat sagu). Menurut penelitian Universitas Gadjah Mada (2023), 70% wisatawan asing mengaku penasaran mencicipi hidangan setelah membaca penjelasan berbahasa daerah. Chef Ragil Imam Wicaksono, peraih penghargaan ASEAN Culinary Award, bahkan menyebut bahasa lokal sebagai “bumbu rahasia” yang memperkaya narasi kuliner Indonesia di kancah internasional.
Startup lokal seperti “Linguaverse” mengembangkan aplikasi translator khusus bahasa minoritas, seperti Bahasa Rejang (Bengkulu) dan Bahasa Sasak (Lombok). Fitur unggulannya adalah database audio yang diisi langsung oleh penutur asli, memastikan terjemahan tetap kontekstual. Dukungan Kemenkominfo melalui program “Digitalisasi Bahasa Daerah” (2024) mempercepat inisiatif ini. Namun, ahli sosiolinguistik Dr. Aisyah Ramadhani mengingatkan: “Teknologi harus menjadi pelengkap, bukan menggantikan interaksi langsung yang menjadi jiwa pariwisata.”
Kampanye pariwisata berkelanjutan mulai menyelipkan kosakata lingkungan dalam bahasa daerah. Di Taman Nasional Komodo, pemandu menggunakan istilah Manggarai “Lalong Gewang” (penjaga hutan) untuk menyebut relawan konservasi. Konsep ini menginspirasi wisatawan asal Prancis, Jean Dupont, untuk membuat podcast “Echoes of Nusantara” yang menggabungkan cerita lingkungan dengan pelajaran bahasa lokal. “Dengan belajar kata ‘tana’ (tanah) dalam Bahasa Manggarai, saya jadi lebih menghargai upaya konservasi di sini,” ujarnya dalam wawancara dengan National Geographic (2024).
Sumber Referensi:
UNWTO. (2023). Global Tourism Resilience Report.
Chen, L. (2022). Journal of Travel Research.
Google Travel Insights. (2024).
Kemenparekraf RI. (2023).
UNESCO. (2023). Atlas of the World’s Languages in Danger.
Bank Indonesia. (2023). Dampak Bahasa Asing pada Ekonomi Pariwisata.
Universitas Gadjah Mada. (2023). Studi Peran Bahasa dalam Wisata Kuliner.
National Geographic. (2024). Podcast “Echoes of Nusantara”.